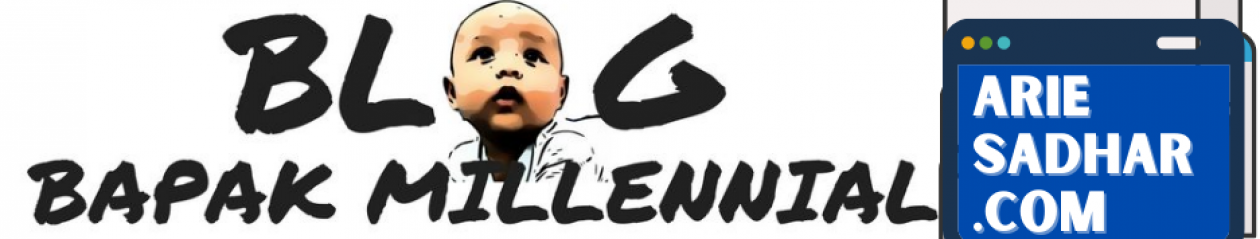Sebagian dari kita mungkin ingat kontroversi cuitan CEO BukaLapak, Achmad Zaky, pada pukul 22.25 WIB tanggal 13 Februari 2019 tentang omong kosong industri 4.0, bujet riset dan pengembangan, serta presiden baru. Sebagian lagi mungkin mengingat dampaknya yang cukup panjang. Pertama, tentu saja perkembangan tagar #UninstallBukaLapak yang bekalangan jadi semakin politis karena kata ‘BukaLapak’ malah diganti dengan ‘Jokowi’, padahal jelas-jelas Jokowi adalah Presiden, bukan aplikasi, jadi ya nggak mungkin di-uninstall, toh?
Kedua, Zaky sendiri sampai datang ke istana karena Jokowi khawatir bahwa tagar untuk meng-uninstall aplikasi yang belum lama di-endorse olehnya itu akan berdampak pada para penjual. Yha, bagi yang doyan belanja daring sih pasti paham bahwa mayoritas penjual itu punya toko di sekurang-kurangnya 3 marketplace besar di Indonesia alias kalau satu ditinggal, tokonya masih bisa dikunjungi via marketplace lainnya.
Ketiga, publik penggerak #UninstallBukaLapak ternyata sama saja pemikirannya dengan #UninstallTraveloka cuma gara-gara hal sepele. Lebih parah lagi, malah jadi lupa pada substansi.
Walaupun ditengarai datanya salah tahun, namun poin Zaky pada pentingnya bujet riset dan pengembangan itu sudah selayaknya jadi perhatian. Supaya isunya tidak seliar cuitan pria Solo tersebut, mari kita coba tempatkan pembahasan pada sektor yang sangat riil kebutuhan akan riset dan pengembangannya yakni industri kesehatan. Lebih spesifik lagi: industri farmasi.
Konsep Riset Industri Farmasi
Saya beruntung pernah hampir 5 tahun berkecimpung di sebuah industri farmasi papan atas Indonesia yang menguasai pangsa pasar obat generik berlogo namun juga pemiliknya cukup edan untuk memiliki sebuah unit riset tersendiri dengan bujet setahun yang nilainya bisa menghidupi sebuah industri farmasi kecil. Dengan demikian, saya bisa cukup percaya diri dalam mengurai perkara riset dalam konteks kefarmasian.
Bagaimanapun, industri farmasi itu unik karena yang dihadapi tidak hanya kompetitor bisnis, namun juga perkembangan penyakit hingga pemutakhiran data keamanan suatu obat sehingga kemudian peran riset dan pengembangan alias R&D menjadi sangat penting.
Apabila pada industri makanan dan kosmetik, R&D bisa dikembangkan ke arah variasi produk seperti rasa maupun warna—hingga kemudian kita bisa mendapati mi instan rasa rendang atau keripik rasa mi instan, misalnya, maka berbeda halnya dengan industri farmasi.
Para peneliti farmasi sejak mula mengembangkan suatu molekul dengan target yang jelas, yakni mengobati suatu penyakit. Metode yang digunakan memang semakin modern dan semakin menggunakan pendekatan bioteknologi untuk hasil yang lebih optimal. Namun tetap saja harus ada harga yang dibayar untuk itu.
Biaya riset menjadi besar setidaknya karena 4 hal, yakni teknologi yang digunakan, bahan aktif baru yang lebih kompleks, fokus riset pada penyakit kronis dan degeneratif dengan biaya yang lebih mahal, dan persyaratan regulatori yang lebih ketat. Dikutip dari penelitian mantan Kepala BPOM, Sampurno, dengan judul ‘Kapabilitas Teknologi dan Penguatan R&D: Tantangan Industri Farmasi Indonesia’ yang dimuat pada Majalah Farmasi Indonesia (2007) estimasi biaya yang dikeluarkan untuk penelitian sejak dari laboratorium hingga dipasarkan pada tahun 1979 adalah 54 juta dolar, sedangkan pada tahun 2003 meningkat menjadi 897 juta dolar. Itupun, tingkat keberhasilannya terbilang rendah. Artikel yang sama menyajikan data bahwa pasca Uji Klinis Tahap III, hanya 20% molekul obat baru yang disetujui untuk diproduksi dan dipasarkan. Forbes pada tahun 2017 menyitir beberapa riset terbaru dan kisarannya sudah semakin dahsyat, bisa mencapai 2,7 miliar dolar per produk!
Makanya, saya suka berpikir kalau di grup WhatsApp ada yang bilang bahwa suatu penyakit adalah konspirasi suatu negara atau kalangan agar mereka bisa menjual obatnya atau suatu obat diarahkan untuk wajib karena ingin membunuh generasi suatu bangsa. Dalam pola pikir ilmiah dan bisnis, kedua konspirasi itu sungguh sangat tidak relevan dan hanya akan terpikirkan oleh otak yang penuh dengan kebencian.
Faktanya COVID-19 sekarang ini sampai nyaris 5 bulan belum ada obatnya. Sampai-sampai obat Ebola yang belum kelar uji klinik diberdayakan.
Biaya riset yang tinggi untuk suatu molekul obat itu tentu saja membutuhkan perlindungan. Tidak ada entitas bisnis yang cukup dungu membiarkan hasil risetnya ditiru dengan serta merta oleh pesaing. Maka dalam dunia farmasi dikenal adanya perlindungan paten. Dampaknya tentu saja adalah harga yang tinggi sebagai upaya untuk balik modal biaya riset dan juga sarana untuk meraih keuntungan sebagaimana hakikat sebuah industri pada umumnya. Begitulah yang terjadi di luar negeri.
Riset Farmasi di Indonesia
Masih menurut Sampurno, di Indonesia agak berbeda karena industri farmasi adalah industri formulasi, bukan research-based company. Kegiatan R&D lebih banyak dilakukan untuk pengembangan formula produk dengan mengandalkan obat-obat yang sudah atau akan segera habis masa patennya. Misalkan untuk obat diabetes Metformin, R&D akan difokuskan pada pencarian kombinasi zat aktif dan eksipien yang akan memberikan hasil paling optimal pada proses produksi, paling mendekati standar kualitas yang telah ditetapkan, serta juga paling efisien dari sisi akuntansi.
Meski begitu, masih ada beberapa pemilik perusahaan yang cukup gila dalam inovasi. Kantor saya dulu, misalnya, berani membayar ratusan miliar untuk mendirikan gedung riset berbasis bahan alam Indonesia, termasuk juga memanggil pulang anak bangsa yang lama berkecimpung dalam riset di luar negeri—tentu saja dengan bayaran yang memadai dan berarti cost yang tinggi bagi perusahaan.
Riset yang baik tentu didukung oleh penelitian tentang kebutuhan obat yang tepat, metode berbasis bioteknologi dan komputasi yang baik, alat-alat yang mutakhir, periset yang kompeten, bahan baku riset yang cukup untuk bereksplorasi, fasiilitas untuk memadai untuk upscaling dari skala laboratorium ke skala industri, fasilitas produksi yang terkini, hingga pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan baik oleh regulator maupun oleh calon mitra tujuan ekspor. Sekali lagi, itu semua butuh cost.
Perlu lebih dari 5 tahun hingga unit riset tersebut bisa menelurkan suatu produk sampai ke pasar dan itupun setelah melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah terutama dari aspek regulasi. Ketika itu, tidak ada insentif khusus, misalnya, karena riset bahan alam Indonesia maka ada tahap-tahap yang boleh dilewati. TIdak ada sama sekali. Kalaulah ada yang agak bisa membanggakan adalah pengembangan unit riset tersebut menjadi salah satu pabrik pertama di Indonesia yang diakui sebagai Industri Ekstrak Bahan Alam dengan peresmian yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan berikut Plt. Kepala BPOM pada tahun 2013 silam.
Proses registrasi produk hasil riset sendiri berjalan sesuai dan sejalan dengan regulasi yang ditetapkan. Begitulah, untuk proses yang sepanjang itu, dipastikan butuh perusahaan yang cukup kuat secara finansial dan pemimpin yang cukup nekat untuk terus menggelontorkan bujet pada risetnya, yang belum tentu balik modal dengan segera.
Tidak Dapat Kompromi Pada Mutu
Sekali lagi, industri farmasi punya kekhasan, yakni tidak dapat kompromi pada 3 hal yakni keamanan, mutu, dan khasiat. Hal itulah yang menyebabkan proses registrasi dari produk yang merupakan hasil karya anak bangsa sekalipun juga harus mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan tanpa perlakuan khusus. Pada posisi ini, pemerintah harus menjalankan beberapa peran sekaligus yakni mendukung sektor industri pada satu kaki, mendukung tambahan terapi pada sektor kesehatan pada kaki yang lain, namun juga harus menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk tersebut pada kaki yang lain lagi.
Aspek mutu ini juga bersisian dengan daya saing. Pada era persaingan bebas, banyak negara menyiapkan perlindungan kepada warganya untuk tetap bisa mendapatkan produk yang bermutu dengan menerapkan pagar berupa standar yang tinggi kepada suatu produk agar bisa masuk ke pasar negara tersebut. Demikian juga dengan sektor farmasi. Walhasil, industri farmasi nasional yang memiliki pasar di luar negeri, mulai ASEAN hingga Eropa harus senantiasa menerapkan standar yang tinggi agar bisa memenuhi standar yang diterapkan di negara tujuan. Dan siapapun tahu, semakin tinggi kualitas yang diharapkan, maka biaya juga akan menyesuaikan.
Ihwal biaya baik untuk riset maupun untuk kualitas yang berstandar internasional ini di Indonesia akan sangat terkait dengan pendapatan suatu industri farmasi yang dalam konstelasi tata kelola kesehatan di Indonesia akan begitu lekat pada isu yang selalu hangat: BPJS Kesehatan.
Sebagai perlindungan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan memang masih memiliki segudang pekerjaan rumah untuk pembenahan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, BPK RI pun telah melakukan pemeriksaan kinerja pada layanan BPJS Kesehatan ini. Persoalan tentang tersendatnya pembayaran dari BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit menjadi salah satu perkara yang sering diangkat ke publik.
Pada konteks ini, industri farmasi dipastikan terkena dampaknya. Obat sebagai produk industri farmasi hanyalah salah satu komponen dari pelayanan kesehatan. Artinya, terhadap pembayaran yang tersendat ke rumah sakit akan berdampak pula pada pembayaran obat ke industri farmasi dan kalaupun pembayaran sudah dilakukan boleh jadi akan dialokasikan terlebih dahulu untuk pembayaran listrik atau air hingga tenaga kesehatan, baru kemudian obat. Bagi industri, pembayaran yang tersendat berarti uang yang diam dan tidak dapat diapa-apakan, padahal ada potensi untuk dikelola salah satunya pada riset dan pengembangan.
Jadi, ketika pendiri BukaLapak membawa isu R&D ke ranah netizen nan kejam dan terlalu fokus pada tahun data dan perkembangan angka, sejatinya problematika R&D itu sendiri telah sedemikian rumitnya di industri farmasi. Persoalannya bukan lagi sekadar besarnya dana sehingga butuh komitmen bersama dari elemen pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, industri farmasi maupun yang relevan dengan dunia kesehatan lainnya, hingga stakeholder lain untuk bisa mengurai problematika riset dalam rumit serta ganasnya gorengan isu kesehatan di negeri ini.
Satu hal yang pasti, untuk membahas soal ini kita tidak perlu membawa-bawa politik yang sarat kepentingan. Bukan apa-apa, kepentingan rakyat dalam persoalan kesehatan itu saja sudah begitu besar dan lebih dari cukup untuk menjadi dasar berpikir bersama demi kesehatan dan industri farmasi Indonesia yang lebih baik.